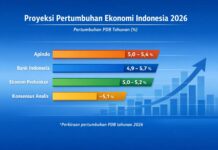bongkah.id — Kasus pengusiran paksa terhadap Elina Widjajanti (79) bukan sekadar sengketa tanah biasa. Peristiwa yang terjadi di siang bolong, disertai kekerasan fisik, perobohan rumah tanpa putusan pengadilan, serta dugaan keterlibatan ormas Madas, telah membuka kembali luka lama tentang praktik premanisme yang berlindung di balik bendera organisasi.
Viralnya video pengusiran Elina di media sosial memantik kemarahan publik. Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Pemuda Surabaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi.
Mereka menuntut pemerintah daerah dan aparat penegak hukum bersikap tegas dengan membubarkan ormas yang terbukti melakukan kekerasan, intimidasi, dan praktik premanisme yang meresahkan warga.
Dalam aksinya, massa juga mendesak kepolisian mengusut tuntas aktor intelektual di balik pengusiran paksa tersebut. Usai berorasi, sebagian peserta aksi bahkan melakukan razia sepihak dengan menurunkan atribut Madas di sejumlah titik di Surabaya—sebuah ekspresi kemarahan warga yang sekaligus mencerminkan rapuhnya rasa keadilan di tingkat akar rumput.
Negara Absen di Saat Kritis
Sosiolog Universitas Airlangga, Tuti Budirahayu, menyayangkan peristiwa yang menimpa Elina. Menurutnya, pengusiran paksa dan perobohan rumah tidak mungkin dibenarkan dalam negara hukum tanpa melalui proses peradilan.
Lebih mengkhawatirkan lagi, kejadian itu berlangsung tanpa kehadiran aparat negara di tingkat paling dasar.
“Seharusnya ada RT, kelurahan, atau polisi yang mencegah tindakan kekerasan itu. Penyitaan rumah wajib melalui proses hukum dan harus diawasi aparat. Ini yang menjadi pertanyaan besar: kenapa tidak ada?” ujar Tuti.
Ia memahami kemarahan warga terhadap ormas yang dianggap telah melampaui batas. Namun, Tuti mengingatkan bahwa secara prinsip, ormas adalah wadah sah bagi warga negara untuk berkumpul dan menyuarakan aspirasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
“Masalahnya muncul ketika ormas disalahgunakan. Ia dijadikan tameng oleh kelompok tertentu, bahkan merekrut preman. Di sinilah fungsi ormas dibelokkan dari tujuan awalnya,” jelasnya.
Jika dibiarkan, lanjut Tuti, praktik semacam ini berpotensi memicu konflik sosial yang lebih luas, bahkan konflik antargolongan.
Karena itu, ia menegaskan bahwa polisi dan pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam ketika menerima laporan adanya aksi anarkistis dan premanisme berkedok ormas.
Pemkot Surabaya:
Tidak Ada Ruang bagi Premanisme
Menanggapi keresahan publik, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan sikap keras pemerintah kota. Ia menyatakan tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi praktik premanisme dalam bentuk apa pun di Surabaya.
Eri bahkan menyatakan siap merekomendasikan pembubaran ormas yang terbukti terlibat dalam kekerasan dan pemaksaan terhadap warga.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Surabaya membentuk Satuan Tugas Anti-Premanisme yang melibatkan unsur TNI, Polri, serta perwakilan berbagai suku dan elemen masyarakat.
“Kita tidak ingin ada premanisme atau kegiatan apa pun yang meresahkan masyarakat. Kalau ada, kita lawan bersama. Tapi jangan sampai terjadi benturan antarsesama warga. Kondusivitas Surabaya harus dijaga,” tegas Eri.
Ia juga berencana mengumpulkan seluruh ormas yang terdaftar di Surabaya—yang jumlahnya mencapai 275 organisasi untuk mempertegas komitmen bersama memberantas premanisme.
Legalitas dan rekam jejak ormas, menurutnya, harus disisir ulang. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas patut dipertimbangkan.
Kronologi Kekerasan
Kasus ini berawal dari klaim sepihak seorang pria bernama Samuel Ardi Kristanto yang mengaku telah membeli tanah milik Elina dari kakaknya, Elisa Irawati, pada 2014. Padahal, Elisa telah meninggal dunia pada 2017 dan tanah tersebut diwariskan kepada Elina.
Pada 6 Agustus, sekitar 50 orang mendatangi rumah Elina di Dukuh Kuwukan, Lontar, Sambikerep. Elina menolak menunjukkan Letter C karena khawatir dirampas. Cekcok pun terjadi.
Ia kemudian diangkat secara paksa oleh beberapa orang dan diusir keluar rumah. Salah satu pelaku yang disebut Elina, Muhammad Yasin, mengenakan kaos merah bertuliskan “Madas Malika”.
Tak berhenti di situ, rumah Elina dipalang, barang-barangnya dipindahkan secara paksa, bahkan bangunan tersebut dirobohkan menggunakan alat berat tanpa perintah pengadilan.
Belakangan, kuasa hukum Elina menemukan sejumlah kejanggalan administrasi, termasuk dugaan akta jual beli palsu dan pencoretan Letter C tanpa melibatkan ahli waris.
Ormas Bantah, Hukum Tetap Berjalan
Pimpinan ormas Madas menyatakan tindakan Yasin tidak terkait dengan organisasi dan mengutuk segala bentuk premanisme. Namun, bantahan ini tidak menghentikan proses hukum.
Polda Jawa Timur telah menetapkan Samuel Ardi Kristanto dan Muhammad Yasin sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran Pasal 170 KUHP. Samuel telah ditangkap, sementara Yasin masih dalam pengejaran.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim, Kombes Pol. Widi Atmoko, menegaskan bahwa penyidikan masih berkembang dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru.
Premanisme Bukan Ekspresi Budaya
Kasus Elina menjadi cermin buram bagaimana kekerasan dapat tumbuh subur ketika hukum kalah cepat dari intimidasi.
Premanisme yang berlindung di balik atribut ormas bukan hanya merusak kepercayaan publik terhadap organisasi kemasyarakatan, tetapi juga mencederai wibawa negara.
Di sinilah pentingnya negara hadir secara tegas, adil dan konsisten. Penegakan hukum yang transparan bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan rasa keadilan korban dan mencegah konflik sosial yang lebih luas.
Surabaya, dan Indonesia tidak boleh membiarkan hukum jalan tertatih sementara premanisme berlari kencang. (kim)