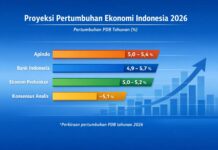bongkah.id – Mulai 2 Januari 2026, Indonesia resmi memasuki babak baru penegakan hukum dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru serta revisi KUHAP.
Pemerintah menyebutnya sebagai tonggak dekolonialisasi hukum, namun di ruang publik, lonceng kewaspadaan justru berbunyi nyaring.
Banyak pengamat, aktivis, dan akademisi menilai sejumlah pasal dalam regulasi baru ini berpotensi menggerus kebebasan sipil dan memperlemah demokrasi.
Salah satu kritik paling tajam datang dari Henri Subiakto, pengamat komunikasi politik. Ia menilai, semangat pembaruan hukum tidak diiringi dengan perubahan paradigma aparat penegak hukum.
“Kita seperti sedang mengulang trauma lama. Norma hukumnya baru tapi watak kekuasaannya terasa lama,” ujarnya.
Pasal Sensitif, Tafsir Elastis
Sorotan utama tertuju pada kembalinya pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Norma yang sebelumnya dicabut Mahkamah Konstitusi kini hadir kembali dengan redaksi baru dalam KUHP.
Frasa “menyerang kehormatan atau martabat” dinilai memiliki tafsir yang sangat luas dan berisiko menjerat ekspresi kritik, demonstrasi, hingga unggahan warganet di media sosial. Bagi kelompok masyarakat sipil, pasal ini menjadi simbol kemunduran.
Kritik terhadap penguasa yang seharusnya menjadi vitamin demokrasi justru berpotensi diperlakukan sebagai tindak pidana. “Jika kritik bisa ditafsirkan sebagai penghinaan, maka garis antara kontrol publik dan kriminalisasi menjadi kabur,” kata Henri.
Tak hanya itu, pasal penghinaan ringan yang dahulu dikenal sebagai Pasal 315 KUHP lama, kini muncul kembali dalam Pasal 436 KUHP baru. Pasal ini membuka peluang pidana bagi ucapan kasar di ruang publik atau media sosial, termasuk umpatan sehari-hari yang selama ini dianggap ekspresi spontan.
Ancaman pidana hingga enam bulan penjara atau denda puluhan juta rupiah membuat banyak pihak khawatir hukum berubah menjadi alat membungkam, bukan melindungi.
Risiko Overkriminalisasi
Kekhawatiran tak berhenti di situ. Pasal-pasal lain seperti penodaan agama dan larangan penyebaran ideologi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila juga dinilai rawan disalahgunakan, terutama terhadap kelompok minoritas dan aktivis kritis.
Dalam praktik penegakan hukum yang masih sarat problem, norma yang lentur justru sering ditarik mengikuti kepentingan politik dan ekonomi.
Henri menilai, problem utamanya bukan semata pada teks undang-undang, melainkan pada budaya penegakan hukum. “Aparat kita sering menafsirkan pasal secara pas-pasan dengan kasus. Keadilan dan kepastian hukum menjadi korban,” tegasnya.
KUHAP Baru dan Bayang-bayang “Superpower” Aparat
Di sisi lain, KUHAP baru juga menuai kritik tajam. Perluasan kewenangan kepolisian bahkan TNI dalam penangkapan, penggeledahan, dan penyidikan dikhawatirkan menciptakan ketimpangan relasi antara negara dan warga. Tanpa pengawasan yang kuat, kewenangan ini berpotensi melahirkan abuse of power dan praktik represif yang lebih sistemik.
Masalah kian kompleks karena kesiapan implementasi dinilai minim. Aturan turunan belum lengkap, sosialisasi terbatas, sementara wilayah Indonesia yang luas menyimpan tantangan besar.
Di atas kertas, KUHAP baru menjanjikan perlindungan HAM dan pendekatan restorative justice, namun di lapangan, kesiapan aparat menerapkan pendekatan tersebut masih diragukan.
Pemerintah dan sebagian DPR menegaskan bahwa KUHP–KUHAP baru adalah wujud kemandirian hukum nasional, menggantikan warisan kolonial Belanda. Mereka menonjolkan pasal-pasal pidana alternatif, kerja sosial, dan keadilan restoratif sebagai bukti modernisasi sistem hukum. tak
Namun bagi para pengkritik, narasi indah itu belum menjawab kegelisahan utama, pasal-pasal sensitif yang mudah disalahgunakan di tengah tren kemunduran demokrasi.
“Hukum yang baik bukan hanya soal niat, tapi juga soal siapa yang menjalankan dan bagaimana kekuasaan dikontrol,” ujar Henri.
Jalan Terakhir: Judicial Review
Di tengah minimnya respons penguasa terhadap kritik publik, banyak pengamat menilai judicial review ke Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya jalan yang realistis. Uji materi diharapkan mampu menyaring pasal-pasal bermasalah agar tidak menjadi alat represi baru.
Henri pun mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada, terutama di ruang digital. “UU ITE saja yang sudah sering dikritik masih bisa ditarik ke mana-mana. Dengan tambahan pasal KUHP baru, risikonya jelas lebih besar jika pola aparat tidak berubah,” katanya.
Berlakunya KUHP dan KUHAP baru seharusnya menjadi momentum memperkuat keadilan dan demokrasi. Namun tanpa koreksi serius, regulasi ini justru berpotensi menjadi alarm keras bagi kebebasan sipil.
Sejarah telah memberi pelajaran mahal, bahwa hukum yang tidak diawasi bisa menjelma menjadi senjata kekuasaan. Kini, publik menunggu, apakah negara mau mendengar atau kembali menutup telinga. (kim)